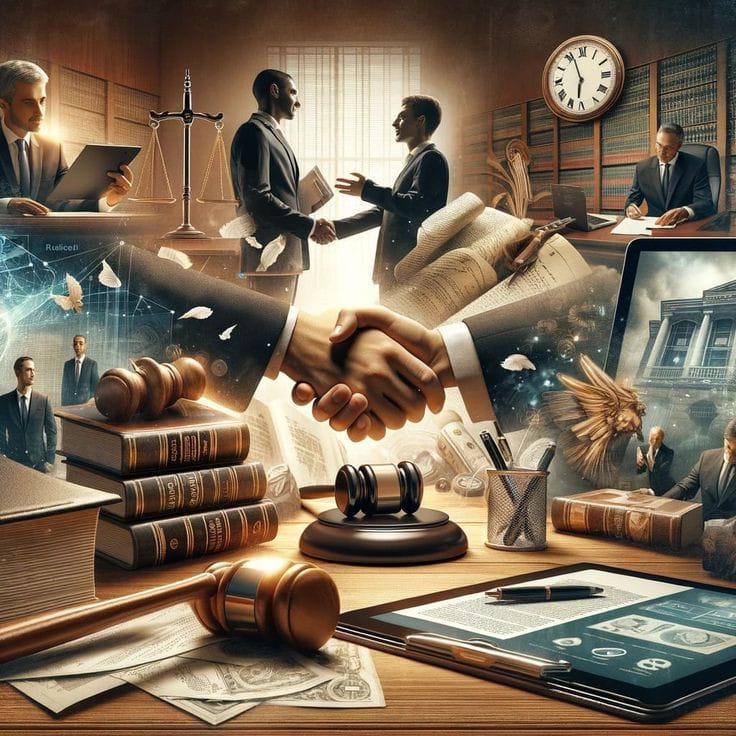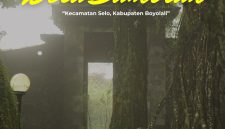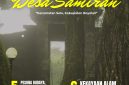Setiap hari, jutaan informasi beredar begitu cepat di dunia digital, khususnya melalui platform populer seperti Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, dan lainnya. Media sosial, yang sering disebut sebagai ruang ekspresi oleh generasi saat ini, seharusnya menjadi tempat berbagi informasi yang bermanfaat dan membawa dampak positif.
Namun, kenyataannya, ada oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan media sosial untuk menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian. Informasi palsu ini menyebar dengan sangat cepat karena pengguna sering kali memberikan komentar tanpa berpikir kritis atau logis, sehingga banyak yang termakan hoaks tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu.
Fenomena ini semakin diperparah dengan rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia. Menurut UNESCO, hanya 0,001% masyarakat Indonesia yang memiliki kebiasaan membaca. Artinya, hanya satu dari seribu orang yang rajin membaca. Tingkat literasi yang rendah ini membuat masyarakat rentan terhadap hoaks, karena mereka cenderung menerima informasi mentah-mentah tanpa mencari kebenarannya terlebih dahulu.
Penyebaran hoaks di Indonesia telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial, ekonomi, dan politik. Penelitian menunjukkan bahwa hoaks adalah informasi palsu atau fakta yang diputarbalikkan dengan tujuan menyesatkan orang lain. Bentuknya bisa berupa berita palsu, gambar yang dimanipulasi, atau narasi yang menyesatkan.
Salah satu kasus yang mencuat adalah disinformasi terkait Pemilu 2024. Pada Februari 2024, beredar pesan berantai di WhatsApp dan Facebook yang mengklaim adanya manipulasi server KPU. Klaim palsu ini memicu kebingungan di masyarakat dan berpotensi menimbulkan konflik.
Data menunjukkan bahwa 92,4% hoaks di Indonesia disebarkan melalui platform seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Pada periode Januari-Februari 2024 saja, terdapat 1.234 konten hoaks yang teridentifikasi. Kerugian yang ditimbulkan sangat besar, baik secara sosial maupun ekonomi, sehingga diperlukan langkah hukum yang tegas untuk menanganinya.
Indonesia telah mengatur penyebaran hoaks melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 28 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016. Pasal ini melarang penyebaran berita bohong yang menyesatkan dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara dan denda hingga Rp1 miliar.
Proses hukum dalam menangani hoaks mencakup beberapa tahap, mulai dari pelaporan oleh masyarakat, verifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), penyelidikan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri), hingga penuntutan di pengadilan.
Masyarakat dapat melaporkan hoaks dengan mengumpulkan bukti seperti tangkapan layar dan URL, lalu mengirimkan laporan ke aduankonten@mail.kominfo.go.id. Setelah laporan diterima, Kominfo akan memverifikasi kebenaran konten tersebut. Jika terbukti melanggar, Polri akan melakukan penyelidikan berdasarkan UU ITE, dan kasus yang telah diselidiki akan dilanjutkan ke kejaksaan untuk diproses lebih lanjut.
Meskipun regulasi ini memberikan dasar hukum yang jelas, efektivitasnya dalam mencegah penyebaran hoaks masih perlu ditingkatkan. Penegakan hukum seperti patroli siber dan edukasi masyarakat masih rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami konsekuensi hukum dari menyebarkan hoaks. Selain itu, pendekatan teknologi dan literasi digital juga harus ditingkatkan agar lebih efektif dalam menangkal hoaks.
Kesadaran kolektif untuk memerangi hoaks harus dibangun melalui sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan. Upaya ini dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan dan seminar untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan memverifikasi informasi.
Kolaborasi dengan influencer juga penting, karena mereka dapat menyampaikan pesan-pesan positif kepada audiens yang lebih luas. Penyediaan sumber daya verifikasi, seperti platform atau aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk memeriksa kebenaran informasi, juga menjadi salah satu langkah yang efektif.
Selain itu, kampanye kesadaran di media sosial perlu digalakkan untuk menekankan pentingnya berpikir kritis dan memeriksa sumber informasi sebelum membagikannya. Pengguna media sosial harus dilatih untuk lebih selektif dalam menyebarkan informasi. Jika setiap individu memiliki kesadaran akan pentingnya literasi digital, dampak penyebaran hoaks dapat diminimalkan.
Pemerintah, sebagai pemangku kebijakan, juga perlu meningkatkan koordinasi antar-institusi agar penanganan kasus hoaks dapat dilakukan dengan lebih efisien. Platform digital harus diajak bekerja sama untuk memonitor dan menghapus konten-konten yang mengandung informasi palsu.
Dalam konteks ini, peran teknologi sangat penting. Teknologi dapat digunakan untuk mengembangkan algoritma yang mampu mendeteksi hoaks secara otomatis. Namun, teknologi saja tidak cukup. Harus ada sinergi antara teknologi, regulasi hukum, dan kesadaran masyarakat.
Hoaks bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah sosial yang membutuhkan pendekatan holistik. Pemerintah, masyarakat, dan platform digital harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan bebas dari informasi palsu.
Fenomena hoaks di Indonesia adalah masalah kompleks yang memerlukan penanganan komprehensif. Meskipun regulasi hukum telah ditetapkan untuk mengatasi penyebaran hoaks, implementasinya masih membutuhkan peningkatan dalam beberapa aspek, seperti sosialisasi, koordinasi antar-institusi, dan efisiensi dalam menjaring pelaku.
Keberhasilan penanganan hoaks tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ekosistem digital yang sehat. Literasi digital harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa masyarakat Indonesia mampu menghadapi tantangan era informasi dengan bijak.
Dengan demikian, upaya bersama ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif hoaks dan menciptakan masyarakat yang lebih kritis, tanggap, dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial.
Penulis : Annisa Rahma Febuana / Prodi KHukum / Universitas Dharmas Indonesia
Editor : Anisa Putri