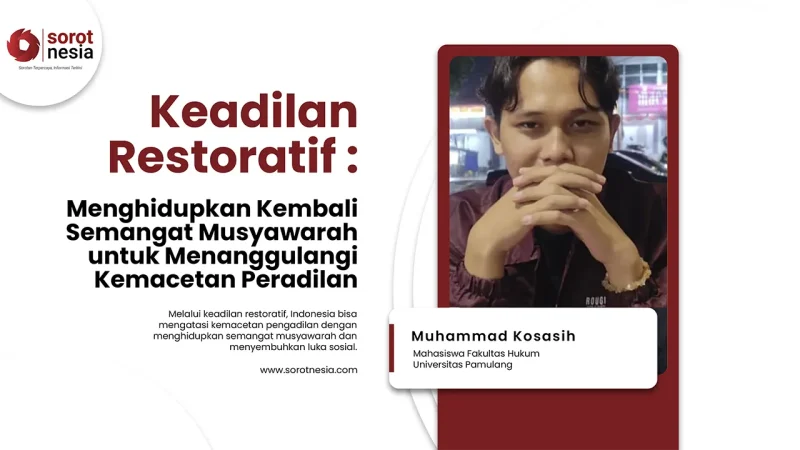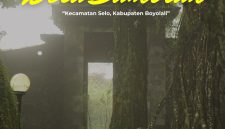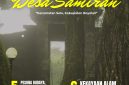Coba bayangkan, seorang pemuda di pinggiran Jakarta terlibat perselisihan kecil dengan tetangganya hanya soal parkir. Alih-alih langsung menyeretnya ke meja hijau yang penuh antrean dan birokrasi melelahkan, keduanya diajak duduk bersama di hadapan orang tua, tetangga, dan seorang mediator lokal untuk berbicara dari hati ke hati.
Hasilnya? Permintaan maaf tulus, kompensasi sederhana, dan kedamaian jangka panjang. Kisah itu bukan sekadar dongeng idealis, melainkan potret yang bisa kita wujudkan secara lebih masif di Indonesia.
Sebab sekarang kita menghadapi fakta berat: pengadilan kita tenggelam di lautan perkara. Menurut data Mahkamah Agung, pada akhir 2023 terdapat lebih dari 4,5 juta perkara yang menumpuk. Proses hukum sering terasa seperti maraton tanpa garis finish.
Banyak warga terutama yang berpenghasilan rendah merasa frustrasi karena penyelesaian lewat jalur formal sering mahal, panjang, dan kadang jauh dari makna rekonsiliasi. Sebagai mahasiswa hukum di Universitas Pamulang, saya terpanggil untuk menawarkan satu gagasan: menjadikan keadilan restoratif sebagai jalan keluar, yang memadukan kearifan lokal dan sentuhan modern, sekaligus mengembalikan spirit gotong royong dalam menyelesaikan konflik sehari-hari.
Di negeri yang kaya keragaman ini, konflik bukanlah hal asing. Dari sengketa tanah di pedalaman hingga perselisihan antar tetangga di kota padat, seringkali kasus besar bermula dari salah paham kecil yang membesar karena kurangnya dialog. Sistem pengadilan formal memang penting, tetapi dalam praktik banyak hambatan: birokrasi yang rumit, sumber daya yang terbatas, dan waktu penyelesaian yang panjang.
Komisi Yudisial menyebut bahwa rata-rata waktu penyelesaian perkara perdata mencapai 18 bulan, sementara biaya litigasi bisa menyedot jutaan rupiah hal yang terutama membebani masyarakat bawah.
Akibatnya, dalam survei nasional terbaru sebanyak 65 persen responden mengaku tidak puas terhadap proses hukum: mereka merasa menjadi “korban ganda” karena konflik tak kunjung usai, bahkan memicu beban baru seperti utang atau stres dalam keluarga.
Inilah titik di mana keadilan restoratif memiliki daya relevansi tinggi. Alih-alih fokus menghukum, keadilan restoratif berorientasi pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan komunitas. Prosesnya melibatkan dialog terbuka, pertanggungjawaban, dan komitmen bersama untuk memperbaiki kerusakan yang timbul.
Konsep ini bukanlah “barang impor” saja; akar gagasannya sudah tumbuh dalam budaya kita. Tradisi silaturahmi di masyarakat Minangkabau dengan pendekatan rekonsiliasi, juga musyawarah desa di Jawa yang menekankan mufakat, mengandung semangat yang sama: menyelesaikan konflik lewat pertemuan dan kesepakatan bersama.
Di Indonesia, langkah awal ke arah restoratif telah dilakukan, meskipun masih dalam fase permulaan. Misalnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberi pijakan penting lewat Pasal 51, yang mendorong penggunaan mediasi restoratif dalam kasus remaja seperti tawuran ringan atau pencurian kecil.
Dalam pendekatan ini, pelaku dapat secara langsung menghadapi korban dalam suasana yang mendorong pengertian: bukan hanya tentang hukuman, tetapi juga empati dan pemulihan. Di Bandung, misalnya, program restorative justice di Pengadilan Negeri berhasil menyelesaikan 75 persen kasus ringan dalam waktu kurang dari tiga bulan, dengan tingkat kepuasan korban mencapai 85 persen (data internal pengadilan).
Di ranah perdata pun, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 membuka peluang bagi mediasi sebelum sidang resmi, memungkinkan pihak-pihak mencapai kesepakatan tanpa melewati proses panjang dan mahal.
Kasus sengketa lingkungan di Kalimantan Selatan tahun 2021 bisa menjadi contoh gemilang. Ketika perusahaan tambang bersengketa dengan masyarakat adat setempat, penyelesaian lewat dialog restoratif yang difasilitasi oleh LSM lokal seperti WALHI membuahkan hasil: kompensasi lingkungan melalui reboisasi lahan dan program pelatihan kerja untuk warga.
Hasilnya tak hanya meredakan ketegangan, tetapi juga mencegah eskalasi menjadi demonstrasi besar atau konflik bersenjata. Yang menarik: pendekatan ini diyakini bisa menghemat negara puluhan miliar rupiah, sekaligus membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang berseteru.
Apa yang membuat keadilan restoratif relevan di masa kini? Kemampuannya menyatukan lokalitas dengan modernitas, menciptakan sistem hukum yang inklusif dan adaptif. Di Nusa Tenggara Timur, misalnya, hukum adat “lili” proses perdamaian melalui upacara adat tetap hidup.
Pemerintah daerah di sana telah mengintegrasikannya dalam prosedur formal melalui otonomi khusus (berdasarkan Pasal 18 UUD 1945), sehingga masyarakat tidak merasa dihukum oleh sistem asing yang tak mereka pahami. Di Flores, sengketa waris sering selesai melalui ritual adat dan doa bersama; sekarang kesepakatan itu juga diformalkan lewat surat agar tidak muncul sengketa ulang.
Sementara itu, di kota-kota besar seperti Surabaya, Medan, atau Jakarta, teknologi bisa memperkaya mekanisme ini. Kementerian Hukum dan HAM bersama startup lokal tengah mengembangkan aplikasi mediasi berbasiskan kecerdasan buatan (AI), yang memungkinkan pihak-pihak berdialog melalui video call dari lokasi berbeda.
Bayangkan konflik hak milik di apartemen Jakarta diselesaikan secara virtual, dengan mediator yang menggabungkan prinsip hukum Islam seperti ta’aruf untuk rekonsiliasi atau adat Jawa agar hasil kesepakatan terasa bermakna secara emosional. Menurut data Badan Litigasi Nasional, pendekatan hybrid seperti ini bisa menurunkan beban pengadilan hingga 30 persen, sekaligus meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap kesepakatan hingga 90 persen, karena pihak-pihak merasa lebih memiliki prosesnya.
Namun, menjanjikan bukan berarti tanpa hambatan. Banyak aparat penegak hukum terlanjur nyaman dengan model konvensional yang bersifat retributif, yang memandang hukuman sebagai bentuk pembalasan. Akibatnya, hanya sekitar 20 persen kasus yang masuk ke jalur mediasi, menurut survei Asosiasi Mediator Indonesia tahun lalu.
Selain itu, dalam konteks Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang tengah dibahas di DPR, ruang untuk keadilan restoratif masih terbatas pada kasus pidana ringan sementara konflik sipil seperti perceraian, waris, atau sengketa kontrak juga memerlukan sentuhan penyelesaian yang mencegah trauma berkepanjangan.
Di Filipina, integrasi restoratif secara nasional telah berhasil menurunkan kekerasan komunal sebesar 40 persen sejak 2010 melalui pelatihan ribuan mediator komunitas; ini bisa jadi pelajaran berharga bagi Indonesia.
Dari sisi kontribusi pribadi, sebagai mahasiswa hukum saya melihat peluang besar. Dalam simulasi mediasi di kampus, saya merasakan langsung betapa kuatnya dialog dalam menjalin keadilan berkelanjutan bukan sekadar menyelesaikan konflik, tetapi juga mencegahnya agar tak terulang.
Untuk memperkuat gagasan ini, saya menawarkan tiga langkah konkret:
Pertama, masukkan kewajiban keadilan restoratif ke dalam RKUHP sebagai tahap pra-sidang untuk semua kasus non-kekerasan berat. Untuk mendukungnya, adakan pelatihan wajib bagi hakim, polisi, dan jaksa melalui kurikulum nasional bekerja sama dengan universitas. Pilot project dapat dimulai di 10 provinsi prioritas agar model ini bisa diuji dan diperbaiki sebelum diterapkan lebih luas.
Kedua, kembangkan pusat mediasi komunitas di tingkat desa atau kelurahan, bekerja sama dengan tokoh adat, lembaga swadaya masyarakat, dan universitas. Hal ini memudahkan akses bagi masyarakat yang jauh dari kota. Untuk korban berpenghasilan rendah, fasilitasi subsidi mediasi melalui dana desa atawa alokasi anggaran daerah.
Ketiga, gencarkan kampanye edukasi publik lewat media digital seperti TikTok, Instagram, YouTube — misalnya seri video singkat bertema “Hukum Ramah Budaya” yang menampilkan kisah sukses lokal. Dengan demikian warga mengetahui opsi alternatif dan berani menggunakannya. Kesadaran masyarakat adalah fondasi agar keadilan restoratif tak hanya tersekat di tataran regulasi, melainkan menjadi praktik hidup di lingkungan.
Akhirnya, keadilan restoratif adalah jembatan emas antara masa lalu yang kaya budaya dan masa depan yang modern. Di tengah beban pengadilan yang terus bergelimpangan dan tuntutan masyarakat yang makin kompleks, mari kita buru kembali semangat musyawarah agar konflik diselesaikan secara adil, manusiawi, dan produktif.
Saya meyakini, jika pemerintah, aparat hukum, akademisi, dan kita warga biasa bersatu langkah, kita bisa menciptakan sistem hukum yang tidak hanya efisien, tetapi juga menyembuhkan luka sosial dan memperkuat relasi antarwarga.
Mulai hari ini, mari kita pilih dialog dalam menghadapi konflik kecil di sekitar kita, dan saksikan transformasi kecil itu menjalar ke komunitas kita. Dengan demikian, keadilan bukanlah milik sekelompok orang, melainkan milik rakyat: seutuhnya, adil, dan menyatu dengan hidup masyarakat.
Penulis : Muhammad Kosasih, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Editor : Anisa Putri