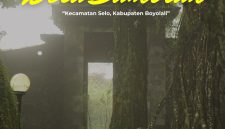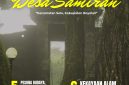Sebagai mahasiswa hukum yang sering berdiskusi di kafe kampus tentang isu lingkungan, saya kerap merenung: bagaimana hukum bisa berperan nyata dalam menyelamatkan planet ini? Perubahan iklim bukan lagi sekadar topik di ruang kuliah ekologi. Ia kini menjadi ancaman yang mengetuk pintu kehidupan sehari-hari.
Indonesia, dengan hutan tropisnya yang luas dan ribuan pulau yang rentan terhadap kenaikan permukaan laut, menghadapi tantangan serius. Emisi karbon dari pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivitas industri menjadi penyumbang besar pemanasan global. Pemerintah pun memperkenalkan pajak karbon sebagai salah satu instrumen pengendalian.
Secara sederhana, pajak karbon berarti: siapa pun yang menghasilkan emisi harus membayar sesuai kadar emisi yang dikeluarkan. Logikanya, ketika polusi dibuat “mahal”, maka orang atau perusahaan akan berpikir ulang dan mencari alternatif yang lebih bersih.
Kebijakan ini diatur melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disahkan pada 2021. Pajak karbon difungsikan sebagai alat hukum untuk menekan emisi, dengan tarif awal ditentukan berdasarkan jenis bahan bakar dan sektor industri.
Pemerintah juga menetapkan bahwa dana yang dihimpun dapat digunakan untuk mendukung transisi energi bersih, reboisasi, serta rehabilitasi lingkungan. Langkah ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Paris Agreement untuk menurunkan emisi hingga 29 persen pada tahun 2030. Namun, pertanyaan kritisnya: apakah pajak karbon benar-benar efektif dan adil bagi semua pihak?
Secara teori, kebijakan ini tampak ideal. Dengan meningkatkan biaya produksi pada industri berpolusi tinggi, seperti PLTU batubara atau pabrik semen, pemerintah mendorong inovasi menuju teknologi ramah lingkungan. Dalam konsep ekonomi lingkungan, ini disebut internalisasi eksternalitas—biaya sosial akibat polusi dialihkan kepada pelaku yang mencemari.
Namun, keindahan teori sering kali runtuh di hadapan realitas implementasi. Efektivitas pajak karbon di Indonesia bergantung pada dua hal: kekuatan hukum dan kesiapan ekonomi. UU HPP memang memberi dasar legal yang jelas, tetapi peraturan pelaksananya masih terus direvisi, bahkan belum memiliki detail teknis yang kuat.
Celah penegakan hukum terbuka lebar, terutama dalam verifikasi emisi ribuan perusahaan di berbagai sektor. Tanpa sistem pemantauan yang transparan dan akurat, pajak karbon berisiko menjadi sekadar formalitas administratif.
Masalah lain muncul dari sisi tarif. Pemerintah mematok pajak karbon sebesar Rp30 per kilogram CO₂e, angka yang terlalu rendah dibandingkan dengan negara-negara Eropa yang mencapai ratusan ribu rupiah per ton. Dalam konteks ini, kebijakan tersebut tampak lebih simbolik daripada fungsional—lebih sebagai sinyal politik daripada instrumen pengubah perilaku.
Selain persoalan hukum, tantangan ekonomi tidak kalah berat. Indonesia masih bergantung pada energi fosil untuk menopang pertumbuhan. Jika pajak karbon diterapkan tanpa peta jalan transisi yang matang, sektor industri bisa terpukul.
Kenaikan biaya produksi hingga 10–20 persen dapat terjadi di sektor tertentu, berimbas pada harga listrik dan bahan bakar. Akibatnya, beban akhirnya jatuh ke pundak masyarakat kecil yang tidak punya pilihan energi bersih.
Di sinilah prinsip keadilan sosial sebagaimana amanat UUD 1945 harus menjadi pijakan. Negara wajib memastikan bahwa kebijakan lingkungan tidak berubah menjadi ketimpangan baru. Pajak karbon harus diimbangi dengan insentif seperti keringanan bagi industri hijau atau subsidi untuk energi terbarukan agar transisi berlangsung adil dan inklusif. Tanpa keseimbangan itu, kebijakan ini berpotensi mencederai semangat keadilan ekologis.
Namun, terlalu dini jika kita menilainya hanya dari sisi risiko. Jika dikelola dengan transparan dan akuntabel, pajak karbon justru bisa menjadi sumber pendanaan baru bagi pembangunan berkelanjutan. Dana tersebut dapat dialokasikan untuk reboisasi, transportasi publik rendah emisi, riset energi bersih, hingga program edukasi lingkungan.
Di sinilah tantangan utama negara: memastikan bahwa setiap rupiah dari pajak karbon benar-benar kembali pada kepentingan lingkungan dan masyarakat, bukan tenggelam dalam birokrasi.
Koordinasi lintas kementerian menjadi faktor kunci. Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian ESDM mesti bergerak serempak, bukan berjalan dalam ego sektoral. Banyak kebijakan lingkungan gagal bukan karena konsepnya salah, tetapi karena antarinstansi lebih sibuk menjaga wilayah kewenangan daripada tujuan bersama.
Dari sisi global, Indonesia juga harus waspada terhadap ancaman carbon leakage perpindahan industri ke negara dengan tarif pajak karbon lebih rendah seperti Vietnam atau Thailand. Jika itu terjadi, investasi bisa menurun dan lapangan kerja berkurang, sementara emisi global tetap tidak berubah.
Yang tak kalah penting adalah kesadaran publik. Sebagian besar masyarakat belum memahami apa itu emisi karbon, apalagi mengaitkannya dengan aktivitas sehari-hari seperti berkendara atau membuang sampah. Tanpa edukasi luas, pajak karbon mudah disalahpahami sebagai beban baru, bukan solusi jangka panjang.
Meski demikian, kita tidak boleh pesimistis. Negara-negara Eropa telah membuktikan bahwa pajak karbon mampu menurunkan emisi dan menumbuhkan inovasi hijau. Indonesia pun memiliki peluang besar dengan potensi energi surya, panas bumi, dan biomassa.
Jika pemerintah memperkuat regulasi, menyediakan insentif transisi, dan mengedukasi publik, pajak karbon dapat menjadi instrumen hukum yang bukan hanya menekan polusi, tetapi juga menegakkan keadilan lingkungan.
Keberhasilan pajak karbon bergantung pada kemauan politik untuk menjadikannya bukan sekadar alat fiskal, melainkan tanggung jawab moral negara terhadap bumi dan generasi yang akan datang.
Penulis : Al Tauhid Iman Siregar | Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Editor : Anisa Putri